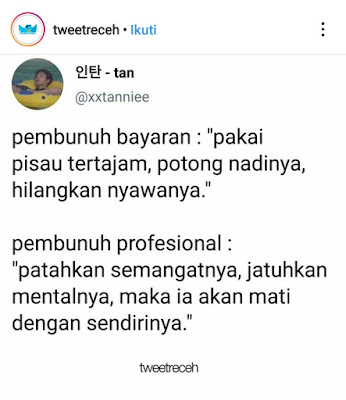Terinspirasi oleh tulisan Mbak Widut tentang merenungi konsep kerja yang halal dan thayyib, saya jadi teringat dengan sebuah kisah di tahun 2011 atau 2012. Memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, melainkan lebih ke makanan yang kita konsumsi. Namun, benang merahnya sama, halal dan thayyib.
Jadi, sekitar tahun 2011/2012, seorang tetangga datang ke rumah kami dan beliau meminta ridho atas semua makanan yang telah beliau ambil dari kebun kami. Dengan mata berkaca-kaca beliau bercerita ketika anak-anak beliau masih kecil, terkadang beliau harus mencari makanan seperti umbi-umbian yang biasanya tumbuh secara liar di kebun-kebun. Nah, hari itu beliau meminta keridhaan kami sebagai anak cucu Uti, agar makanan yang telah beliau makan ketika itu berstatus halal.
Oya, fyi, usia beliau mungkin sepantaran dengan almarhumah Uti.
Saya yang mendengar pengakuan dan permintaan maaf beliau tentu merasa terharu dan sedih sekaligus. Terharu karena, Ya Allah, kami ridho... Timbang gembili atau uwi doang atau apalah itu, ya kan? Sedihnya pun bukan karena makanan, tapi karena jadi bertanya-tanya, apa beliau sudah merasa waktunya sudah dekat? Dan memang, tak lama setelah itu beliau berpulang. Allahummaghfirlaha warhamha wa'aafihi wa'fu'anha.
Ingat kisah itu, jadi ingat juga kisah seorang pemuda dan sebuah apel yang saya baca di republika.co.id. Kisah ini juga diceritakan oleh guru tahsin saya beberapa waktu lalu.
Alkisah, di masa akhir era Tabi'in, hidup seorang pemuda dari kalangan biasa, tetapi memiliki kesalehan yang luar biasa. Pemuda itu bernama Tsabit bin Zutho. Saat itu ia sedang berjalan di pinggiran Kota Kufah, Irak. Karena kelelahan, ia beristirahat di tepi sungai yang jernih. Tiba-tiba, sebuah apel segar tampak hanyut di sungai itu.
Dalam kondisi lapar, Tsabit pun memungut apel tersebut dan menggigitnya. Baru sedikit menikmati apel merah dan manis itu, Tsabit tersentak. Milik siapa apel ini? Bisiknya dalam hati. Meski menemukannya di jalanan, Tsabit merasa bersalah karena telah memakan apel tanpa seizin pemiliknya.
"Bagaimana aku bisa memakan sesuatu yang bukan milikku?" kata Tsabit menyesal.
Ia kemudian menyusuri sungai, mencari pemilik buah apel ini untuk meminta keridhaan-nya atas apel yang sudah digigitnya itu. Cukup jauh Tsabit menyusuri aliran sungai itu, hingga ia melihat sebuah kebun apel. Tsabit segera mencari pemilik kebun itu, tetapi ternyata yang ia temui adalah penjaga kebun.
"Saya bukan pemilik kebun ini. Rumah pemilik kebun ini cukup jauh, sekitar lima mil dari sini," kata sang penjaga kebun.
Walaupun harus menempuh jarak yang cukup jauh, Tsabit tak putus asa. Ini semua demi mencari keridhaan pemilik apel yang telah ia makan.
Akhirnya, ia sampai di sebuah rumah dengan perasaan gelisah. Apakah si pemilik kebun akan memaafkannya? Tsabit merasa takut sang pemilik tak meridhoi apelnya yang telah jatuh ke sungai itu, digigit olehnya.
Tsabit mengetuk pintu, lalu mengucapkan salam. Seorang pria tua, sang pemilik kebun apel, membuka pintu itu.
Tsabit berkata, "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari kebun Anda di tepi sungai, kemudian saya memakannya. Saya datang untuk meminta kerelaan Anda atas apel ini. Apakah Anda meridhoinya? Saya telah menggigitnya dan ini yang tersisa." Ujar Tsabit sambil menunjukkan apel yang telah digigitnya.
Tanpa diduga, sang pemilik kebun berkata, "Tidak, saya tidak merelakannya, Nak."
Tsabit penasaran, mengapa sang pemilik kebun enggan merelakan sebutir apelnya? Toh, apel itu telah jatuh dan hanyut ke sungai.
"Saya tidak memaafkanmu, demi Allah, kecuali jika engkau mau memenuhi persyaratanku." Lanjut sang pemilik kebun.
"Persyaratan apa itu?" tanya Tsabit harap-harap cemas.
"Kau harus menikahi putriku. Putriku itu buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tak mampu berjalan, apalagi berdiri. Kalau kau mau menerimanya, maka saya akan memaafkanmu, Nak." Jawab sang pemilik kebun.
Tsabit terperanjat. Sebegitu besarkah kesalahannya sehingga ia harus menerima hukuman dengan menikahi seorang wanita yang cacat? Namun, Tsabit menerima syarat tersebut karena ia tak ingin berdosa telah mengambil hak yang bukan miliknya.
"Datanglah ba'da Isya untuk bertemu dengan istrimu," kata pemilik kebun.
Malam hari usai salat Isya, Tsabit pun menemui istrinya yang cacat. Dengan langkah yang berat, ia masuk ke kamar pengantin wanita. Hatinya dipenuhi dengan pergolakan yang luar biasa, tetapi pemuda itu tetap bertekad untuk memenuhi syarat sang pemilik apel.
Namun, betapa terkejutnya Tsabit ketika berhadapan dengan wanita yang merupakan istrinya tersebut. Ia bahkan mengira telah salah masuk kamar, karena wanita yang seharusnya merupakan istrinya adalah wanita yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh.
Tsabit bertanya pada wanita di hadapannya, apakah ia benar putri sang pemilik kebun?
Mendapati suaminya mempertanyakan dirinya seolah tak percaya, wanita itu bertanya, "Apa yang dikatakan ayah tentang aku?"
"Ayahmu berkata bahwa engkau adalah seorang gadis buta," kata Tsabit.
"Demi Allah, ayahku berkata jujur. Aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah," jawab wanita itu.
"Ayahmu juga berkata bahwa kamu bisu," ujar Tsabit, masih dipenuhi rasa heran.
"Iya benar, aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Allah murka," jawab wanita yang telah menjadi istrinya itu.
"Tapi, ayahmu mengatakan bahwa kamu bisu dan tuli." Kata Tsabit lagi.
"Ayahku benar. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali di dalamnya terdapat ridho Allah."
"Tapi, ayahmu juga mengatakan bahwa kamu lumpuh."
"Ya, Ayahku benar dan tidak berdusta. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai."
Tsabit begitu terpesona pada istrinya yang tak hanya cantik jelita tetapi juga shalihah itu. Ia pun mengucap syukur.
Ternyata, sesuatu yang sebelumnya dia anggap sebagai hukuman, justru menjadi sebuah nikmat yang tiada terkira. Benar janji Allah, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."
Sang pemilik kebun yang seolah "kejam" itu ternyata kagum dengan sifat kehati-hatian Tsabit dalam memakan sesuatu hingga jelas kehalalannya. Melihat kegigihan dan kesalehan Tsabit, ia pun berkeinginan untuk menjadikannya menantu dengan menikahkannya pada putrinya yang shalihah.
Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang ulama shalih mujadid yang sangat terkenal yakni Nu'man bin Tsabit atau yang lebih dikenal dengan Al Imam Abu Hanifah. Bersama istri yang shalihah, Tsabit mendidik putranya menjadi salah satu imam besar dari empat mazhab.
Ya, itulah kisah tentang kejujuran seorang pemuda dan sebuah apel. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, yaa...
Ditulis dengan Cinta,
Mama